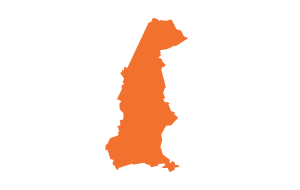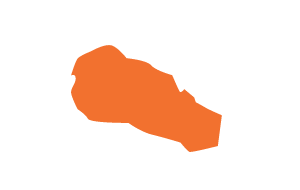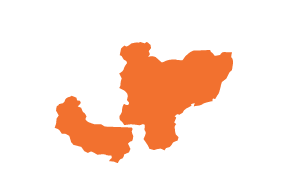Dampak Teritorial dari Ekstraksi Global
Hilangnya Keanekaragaman Hayati dan Perubahan Iklim
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan iklim sangat terkait dengan semakin meluasnya kegiatan pertambangan formal dan informal dan akan tergantung pada apakah ekstraksi dilakukan di darat atau di laut. Untuk kegiatan di darat yang telah lama dilakukan oleh para pemain skala besar dan kecil, endapan timah aluvial diekstraksi setelah pembongkaran vegetasi di atas tanah bagian atas dan pemindahan lapisan tanah penutup yang tidak mengandung timah. Para penambang harus menuangkan sejumlah besar air bertekanan tinggi ke atas endapan untuk memisahkan bijih timah yang berat dari material lainnya. Akibatnya, air bekas dan endapan dari proses pencucian ini menghasilkan bahan asam dengan pH di bawah 3 yang membawa dampak negatif terhadap flora dan fauna.
Keasaman mengubah struktur dan komposisi vegetasi, yang menyebabkan kerusakan yang mengkhawatirkan dan signifikan pada aspek biofisik sumber daya lahan, termasuk perubahan tekstur tanah, hilangnya kesuburan tanah, kerusakan struktur tanah, hilangnya bahan organik tanah, juga penurunan produktivitas tanah dan kualitas lingkungan dalam hal perubahan topografi dan morfologi lahan. Hal ini menyebabkan hilangnya biota yang sangat penting dalam menyediakan jasa lingkungan seperti stabilitas tanah dan penyediaan hasil hutan, serta menjaga penyerapan karbon dan siklus hidrologi. Selain banjir dan rusaknya infrastruktur, sungai yang menerima sedimentasi timah memiliki spesies ikan yang hampir 30% lebih sedikit dibandingkan dengan sungai yang bebas dari kegiatan tersebut.
Sementara itu, penambangan timah lepas pantai ditemukan menurunkan kualitas air dan menyebabkan penurunan jumlah spesies plankton sebesar 40%: jumlah spesies lamun di perairan yang ditambang sekitar 70% dari jumlah yang tidak ditambang; jumlah ikan yang berasosiasi dengan terumbu karang di perairan yang ditambang adalah 30% dari jumlah ikan yang ada di ekosistem yang tidak ditambang; cakupan kehidupan terumbu karang kurang dari 25% di perairan yang ditambang dibandingkan dengan lebih dari 90% di lingkungan yang tidak ditambang. Angka-angka ini sangat signifikan karena kepulauan ini dikenal dengan berbagai sumber daya pesisirnya, seperti terumbu karang, hutan bakau, dan padang lamun.
Pengolahan bijih timah juga berkontribusi terhadap sejumlah besar emisi karbon. Meskipun sering dipahami sebagai mineral yang relatif mudah ditambang, proses pengolahan timah membutuhkan banyak bahan lain selama proses peleburan dan pemurnian untuk mencapai tingkat kemurnian 99,9%. Bahan-bahan tersebut antara lain batu bara, batu kapur, kristalisasi, dan aluminium dalam pembuatan batangan timah murni. Meskipun bahan-bahan tersebut merupakan bahan yang padat karbon, timah semakin dikaitkan dan diintegrasikan dengan wacana keberlanjutan dan kemajuan teknologi transisi energi global. Hal ini menunjukkan bahwa dekarbonisasi di sektor pertambangan timah terutama dipikirkan dalam hal pembangkitan energi, namun peleburan dan pengolahan timah membutuhkan cukup banyak batu bara dan mineral lainnya. Penggunaan aluminium, misalnya, juga dapat dikaitkan dengan narasi ekonomi sirkular yang dapat mengarah pada pencucian hijau (greenwashing) industri ekstraktif. Diperlukan lebih banyak upaya untuk memahami dekarbonisasi industri pertambangan timah untuk melihat hubungannya dengan proyek transisi energi global.
Pengelolaan limbah dari produksi timah masih bermasalah. Para pelaku sering menyebut limbah tersebut sebagai “terak timah”. Perusahaan timah swasta menyebut apa yang mereka lakukan sebagai “material balance” karena mereka memiliki catatan yang terdokumentasi dengan sangat baik, tidak hanya untuk produksi, tetapi juga untuk limbahnya. Perusahaan tersebut memiliki jumlah pasti berapa kg/ton limbah yang mereka hasilkan dari proses peleburan dan pemurnian. Namun, tumpukan limbah tersebut berada di halaman belakang perusahaan dan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Perusahaan harus menyimpan limbah tersebut karena tidak diperbolehkan oleh hukum untuk memindahkan atau mengangkut limbah ke tempat lain di luar perusahaan karena kandungan radioaktifnya. Selain itu, belum ada kebijakan atau teknologi yang dapat mengolah limbah tersebut menjadi bentuk yang lebih ramah lingkungan atau berguna. Akibatnya, perusahaan harus terus menerus meminta izin perluasan lahan untuk menyimpan limbah tersebut.
Dalam kasus perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, konversi lahan yang terjadi cukup signifikan. Khususnya yang berkaitan dengan transformasi lahan menjadi area perkebunan. Menurut sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2016, Indonesia mengalami deforestasi yang signifikan, yang mengakibatkan berkurangnya sekitar 50% dari keseluruhan area hutan akibat ekspansi kelapa sawit.
Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati secara signifikan. Beberapa isu yang menonjol termasuk degradasi habitat orangutan dan harimau, serta dampak buruk terhadap populasi ular dan burung. Perluasan perkebunan kelapa sawit juga mengaburkan hak dan otoritas lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat. Hal ini berdampak pada perubahan peran masyarakat adat beserta hak-haknya yang kini semakin tergerus.
Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas penting dalam perekonomian Indonesia. Presiden Joko Widodo telah menetapkan kelapa sawit sebagai “emas hijau” karena nilai ekonomi strategisnya yang signifikan. Komoditas ini memiliki daya saing yang unggul jika dibandingkan dengan komoditas lain di sektor pertanian. Pada akhir tahun 2022, nilai ekspor komoditas ini diperkirakan akan mencapai 29,66 miliar dolar AS, yang mengindikasikan pertumbuhan yang cukup besar dibandingkan dengan angka yang tercatat pada tahun 2020 (Lihat di bawah). Namun, ekspansi besar-besaran kelapa sawit juga telah menyebabkan kerugian yang signifikan, terutama terhadap lingkungan dan juga mengurangi kekayaan alam Indonesia. Konflik antara masyarakat yang tinggal di sekitar area perkebunan dengan hewan liar juga meningkat dengan dibukanya perkebunan kelapa sawit baru.
Keadilan Lingkungan
Ekspansi besar-besaran kegiatan pertambangan timah dan perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan meningkatnya ketidaksetaraan dan marjinalisasi dalam proses pengambilan keputusan, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan konflik. Pengakuan atas siapa yang diizinkan untuk menambang timah atau menanam kelapa sawit, siapa yang dapat memprosesnya, dan bagaimana mereka ditransfer di sepanjang rantai pasokan tunduk pada berbagai mekanisme pengecualian. Sementara perusahaan-perusahaan besar memiliki pengaruh karena mendapatkan izin dari pemerintah pusat, masyarakat lokal selalu rentan terhadap razia kebijakan karena praktik penambangan timah mereka yang ilegal. Tanpa adanya mekanisme keselamatan dalam prosedur penambangan mereka, para penambang rakyat sering kali harus menanggung semua risiko dan bahaya dari kegiatan penambangan sambil memasok bahan baku kepada perusahaan besar.
Karena sebagian besar lahan untuk kegiatan penambangan timah di Bangka merupakan lahan konsesi yang dimiliki oleh PT Timah Tbk sebagai perusahaan milik negara, para penambang rakyat dan penambang kecil harus bermitra dengan perusahaan untuk dapat melanjutkan produksi mereka. Kemitraan ini memberikan izin kepada penambang kecil untuk dapat menambang di wilayah konsesi PT Timah, dan mewajibkan mereka untuk menjual bijih timah yang telah diekstraksi kepada PT Timah dengan harga yang telah ditetapkan. Namun, terdapat perbedaan harga yang cukup besar untuk penjualan bijih timah tersebut. Harga yang ditetapkan oleh PT Timah seringkali lebih murah daripada harga yang ditawarkan oleh pengepul swasta atau perusahaan peleburan swasta. Namun demikian, para penambang kecil harus menerima kerugian ini sebagai imbalan atas keamanan dan jaminan operasi mereka yang diberikan oleh perusahaan melalui kemitraan. Akibatnya, ketergantungan relatif mereka terhadap perusahaan membuat penambang terpapar pada berbagai lapisan risiko yang terkait dengan perubahan peraturan sepihak oleh pemerintah dan industri.
Kehadiran para pendatang yang dibawa oleh para investor atau pengusaha untuk bekerja di kegiatan pertambangan mereka juga menimbulkan ketegangan sosial dengan masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan terbatasnya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dan membuat mereka, bahkan perempuan, hanya memiliki beberapa kegiatan pendukung operasi pertambangan, seperti perempuan dan anak-anak yang melakukan “ngreman” di mana mereka harus memberikan jasa atau makanan kepada para penambang dengan imbalan bijih timah, atau masyarakat lokal harus mencari sendiri sisa-sisa timah yang ada di anjungan lepas pantai yang dimiliki oleh perusahaan dan menjualnya dengan harga yang sangat rendah.
Namun, pada saat yang sama, baik operasi pertambangan skala kecil maupun besar telah menurunkan jumlah ikan yang bisa ditangkap oleh komunitas nelayan setempat. Tanpa adanya jaminan hasil tangkapan yang baik, tidak mengherankan jika banyak nelayan yang memutuskan untuk menghentikan kegiatan penangkapan ikan dan beralih menjadi penambang. Inilah sebabnya mengapa penambangan timah lepas pantai dianggap merusak lingkungan pesisir dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan kegiatan perikanan tradisional.
Di sisi lain, para petani kelapa sawit berjuang untuk mendapatkan dana untuk mengintensifkan produksi mereka seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masalah kepemilikan lahan merupakan masalah utama bagi para petani kecil mandiri karena mereka harus membuktikan hak mereka atas lahan tersebut untuk mendapatkan akses ke sumber daya keuangan, pengadaan, dan pengetahuan. Meskipun mereka adalah penggerak ekonomi utama untuk mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan terpencil – sebuah isu yang belum dipenuhi oleh agenda pembangunan nasional – petani kecil menghadapi kesulitan untuk memenuhi standar produk kelapa sawit berkelanjutan baik global maupun nasional, seperti Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal ini sering kali membuat mereka terasing dari pasar yang menuntut pemenuhan aspek keberlanjutan di seluruh rantai produksi. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit besar, dengan modal dan investor yang besar, memiliki sumber daya dan kapasitas yang kuat untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar-standar praktik keberlanjutan tersebut, sementara para petani kecil harus beroperasi dengan modal yang sangat terbatas dan akses terhadap berbagai fasilitas yang dapat membantu mereka untuk menjual produk mereka dengan lebih baik.