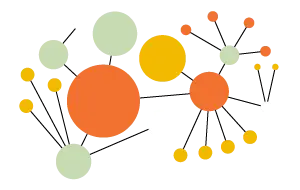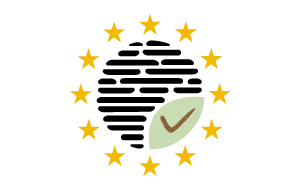TATA KELOLA & KONEKSI YANG MENYIMPANG
Adaptasi Perubahan Iklim
Wilayah Tapajós, Brazil
Perjanjian Paris mulai berlaku pada tahun 2016 dan menetapkan bahwa setiap negara anggota perjanjian akan mengajukan target pengurangan gas rumah kaca (GRK), berdasarkan apa yang disebut sebagai Kontribusi yang Diniatkan Secara Nasional (Intended Nationally Determined Contributions/INDC) (UNFCCC, 2018). Kongres Nasional Brazil menyetujui ratifikasi perjanjian tersebut pada bulan September 2016, mengubah iNDC menjadi komitmen wajib.
Dengan ratifikasi Perjanjian Paris, Brazil berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 37% pada tahun 2025 dan 43% pada tahun 2030, keduanya dibandingkan dengan emisi tahun 2005. Pada tahun yang sama, pemerintah menyiapkan Rencana Adaptasi Perubahan Iklim Nasional (PNA) yang melibatkan 55 kebijakan, rencana, dan program publik di berbagai sektor. Untuk mencapai target pengurangan emisi, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan porsi bioenergi berkelanjutan dalam matriks energinya, merestorasi dan menghijaukan kembali 12 juta hektare hutan, dan mencapai sekitar 45% porsi energi terbarukan dalam komposisi matriks energi pada tahun 2030.
NDC Brazil telah memiliki 3 versi yang diperbarui sejak publikasi aslinya. Pembaruan kedua yang diterbitkan pada tahun 2022 merupakan langkah mundur dalam target pengurangan karena memungkinkan peningkatan sekitar 400 juta ton lebih banyak emisi GRK (WRI, 2022) .
Namun, pada versi ketiga yang diperbarui, pada bulan September 2023, pada KTT Ambisi Iklim, yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, pemerintah Brazil telah mengembalikan tujuan awalnya untuk memiliki batas emisi sebesar 1,32 GtCO2e – konsisten dengan pengurangan 48,4% pada tahun 2025, dan 1,20 GtCO2e – konsisten dengan pengurangan 53,1% pada tahun 2030, dibandingkan dengan emisi tahun 2005. Selain itu, Brazil menegaskan kembali komitmennya untuk mencapai emisi netral bersih pada tahun 2050, yaitu semua emisi yang dikeluarkan oleh negara tersebut harus dikompensasikan dengan sumber-sumber penangkap karbon, seperti penanaman hutan, pemulihan bioma, atau teknologi lainnya. (MMA, 2023).
Hampir setengah dari emisi Brazil berasal dari Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan (LUCF) (48%), diikuti oleh Sektor Pertanian (26%) dan sektor Energi (17%). Negara bagian Pará dan Mato Grosso memimpin peringkat emisi LULUCF (SEEG, 2023).
Dalam empat tahun terakhir, melemahnya kebijakan lingkungan dan pembubaran badan-badan inspeksi lingkungan, yang terkait dengan meningkatnya invasi lahan dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat mengakibatkan peningkatan deforestasi yang signifikan, terutama di wilayah Amazon, tetapi juga di Cerrado dan Pantanal. Namun, dengan pergantian pemerintahan dan dimulainya kembali kebijakan lingkungan, antara Januari dan Agustus 2023, penurunan tingkat deforestasi sebesar 48% tercatat melalui fase baru PPCDAM (Rencana Aksi Pencegahan dan Pengendalian Deforestasi di Amazon). Deforestasi terkait erat dengan sektor agribisnis, karena sebagian besar hilangnya hutan untuk peternakan dan produksi kedelai di Amazon.
Di Wilayah Tapajós, luas area (ha) yang ditanami kedelai secara khusus di Dataran Tinggi Santareno, Transamazonic dan BR-163, di Pará, meningkat 254% antara tahun 2008 dan 2022. Pada kecepatan yang sama, jumlah ternak sapi meningkat dari 1,4 juta menjadi 2,2 juta ekor pada periode yang sama (IBGE, 2023). Meskipun sebagian besar area kedelai tidak berkembang di dalam hutan, hal ini mendorong perluasan padang rumput ke dalam lahan hutan.
Selain mendorong dan mensubsidi implementasi infrastruktur untuk memperluas produksi komoditas ini dan komoditas lainnya, seperti minyak kelapa sawit, negara juga berupaya menunjukkan komitmen terhadap target pengurangan emisi Perjanjian Paris. Sebagai contoh, baru-baru ini Helder Barbalho, Gubernur Pará menandatangani perjanjian untuk bergabung dengan kampanye Race to Zero, sebuah inisiatif global yang bertujuan untuk menyatukan para pemimpin untuk mencapai emisi gas rumah kaca nol pada tahun 2050. Tujuan tersebut harus dicapai melalui tindakan dekarbonisasi, menarik investasi untuk bisnis yang berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja hijau.
Program Akselerasi Pertumbuhan (PAC, singkatan dalam bahasa Portugis, program investasi publik utama dari pemerintahan Lula) memperkirakan investasi sebesar hampir R$39 miliar di Pará. PAC merencanakan 18 proyek infrastruktur transportasi, termasuk pengaspalan dan perbaikan BR-163, penyelesaian jembatan di atas Sungai Araguaia (BR-153) dan pengaspalan serta pembangunan jembatan di beberapa bagian BR-230 (jalan Transamazonic). Di sektor perkeretaapian, investasi direncanakan untuk Kereta Api Carajás dan persiapan studi untuk konsesi EF-170, ke Ferrogrão. Ada juga investasi yang direncanakan di pelabuhan Barcarena, Belem, Santarém dan Vila do Conde, dan di jalur air dengan tujuan untuk meningkatkan transportasi melalui sungai-sungai di Negara Bagian.
Semua investasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur untuk transportasi dan ekspor komoditas, mengkonsolidasikan wilayah tersebut sebagai koridor utara bahan baku yang rendah ke arah utara dunia sehingga merugikan hutan, keanekaragaman hayati, dan masyarakat Amazon. Model ini secara drastis bertentangan dengan target pengurangan emisi dan ekonomi rendah karbon.
Putumayo, Kolombia
Kolombia merupakan salah satu penandatangan perjanjian Paris yang diratifikasi pada tahun 2018. Selain itu, Kolombia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan NDC yang telah direvisi mencakup target mitigasi yang lebih ambisius yaitu 169,4 MtCO2eq pada tahun 2030, yang setara dengan pengurangan emisi sebesar 51% dari skenario referensi 2030 yang telah direvisi (UNDP, 2023). Sebagai perbandingan global, emisi berbasis konsumsi per kapita cukup rendah, yaitu 2 ton per orang pada tahun 2021 (Anggaran Karbon Global, 2023). Meskipun demikian, tantangan utama tetap ada pada perubahan penggunaan lahan dan emisi gas rumah kaca (GRK) terkait kehutanan, yang merupakan sektor yang menghasilkan bagian terbesar GRK di Kolombia (Our World in Data, 2023).
Kolombia telah mengalami lonjakan deforestasi yang substansial selama dekade terakhir yang disebabkan oleh perluasan pertanian industri dan kelapa sawit, kegiatan peternakan di wilayah perbatasan Amazon, dan tanaman terlarang serta proyek-proyek infrastruktur. Terutama setelah Perjanjian Damai antara pemerintah Kolombia dan gerilyawan FARC-EP, deforestasi melonjak di wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali gerilyawan. Dengan memanfaatkan kekosongan otoritas dan kurangnya kontrol negara, dan dengan harapan mendapatkan sertifikat tanah yang sah, para pemilik tanah dan peternak yang berkuasa memperluas kegiatan mereka ke dalam kawasan hutan. Sebagian besar penggundulan hutan terjadi di sepanjang pinggiran barat laut wilayah Amazon, termasuk di departemen Putumayo.
Indonesia
Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi emisi karbon dan pada saat yang sama mendorong proyek-proyek pembangunan yang berpotensi menghambat pemenuhan target tersebut. Berdasarkan Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) yang dirilis pada tahun 2022, Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 1.953 MTonCO2-eq, atau 31,89% lebih rendah dibandingkan dengan emisi gas rumah kaca (GRK) skenario business-as-usual yang mencapai 2.869 MTonCO2-eq pada tahun 2030. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa Indonesia akan mampu mencapai pengurangan hingga 43,2%, dengan syarat adanya dukungan internasional dalam hal pendanaan, transfer dan pengembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas. ENDC merupakan pembaruan dari target NDC yang diumumkan pada tahun 2016, di mana targetnya adalah 29% untuk skenario tanpa syarat dan 41% untuk skenario bersyarat. Selain itu, pemerintah memperkirakan bahwa Indonesia akan mencapai puncak emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 1,2 GtCO2-eq, dan kemudian akan menurun dan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060.
Pengurangan emisi dari kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) diharapkan dapat memberikan kontribusi terbesar terhadap penyerap karbon. Berbagai kebijakan telah dibuat untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan kapasitas penyerapan karbon dari hutan alam, meningkatkan penyerapan karbon dari sistem lahan, serta mengurangi emisi dari kebakaran dan dekomposisi gambut (Kementerian, 2022). Tulang punggung dari target tersebut adalah REDD+. Pada tahun 2015, pemerintah mengajukan Tingkat Emisi Rujukan Hutan (Forest Reference Emission Level/FREL), yang ditetapkan sebesar 0,568 GtCO2-eq dengan mengacu pada periode 1990-2012 untuk mengevaluasi emisi selama 2013-2020. Pada tahun 2022, pemerintah mengajukan FREL kedua sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi tingkat emisi selama periode 2021-2030. Di antara pembaruan penting adalah bahwa tolok ukur baru yang diusulkan memperhitungkan deforestasi, degradasi hutan dan peningkatan stok karbon hutan, dekomposisi gambut, kebakaran (gambut dan mineral) di daerah yang mengalami deforestasi atau degradasi hutan, dan emisi dari konversi hutan bakau menjadi area budidaya. Selain itu, juga menghitung cadangan karbon yang terdiri dari biomassa di atas tanah, biomassa di bawah tanah, kayu mati, serasah, dan tanah. Indonesia juga telah mendorong pengembangan penyimpanan karbon (carbon capture storage/CCS), di mana perusahaan milik negara seperti Pertamina berharap adanya kolaborasi dengan perusahaan internasional (Pertamina, 2023). Pada bulan September 2023, Indonesia secara resmi meluncurkan bursa karbon yang diberi nama IDXCarbon. Bursa karbon ini terhubung langsung dengan sistem registrasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencegah penghitungan ganda. Kendati demikian, bursa karbon ini belum sepenuhnya berjalan.
Namun, di sektor energi, Indonesia telah mengambil pendekatan tengah-tengah, dengan mempertahankan tingkat dukungan tertentu untuk industri bahan bakar fosil. Berdasarkan target ENDC, pengurangan emisi dari sektor energi masih jauh dari ambisius, seperti yang terlihat dari estimasi output GRK dalam skenario tanpa syarat dan bersyarat. Target ini ditetapkan dengan latar belakang bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mendorong pemanfaatan energi terbarukan, mengurangi subsidi bahan bakar, mewajibkan pencampuran bahan bakar nabati ke dalam bahan bakar diesel, dan penggunaan kendaraan listrik. Selain itu, pada tahun 2022, sebuah peraturan presiden dikeluarkan untuk melarang pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara baru, kecuali yang telah disetujui sebelum peraturan tersebut berlaku. Pada tahun 2022, Indonesia juga mendapatkan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP), yang diharapkan dapat mengerahkan dana publik dan swasta sebesar $20 miliar untuk dekarbonisasi. Dalam rencana awal, JETP bertujuan untuk membatasi emisi karbon dari sektor listrik hingga 290 MTonCO2-eq pada tahun 2030, menetapkan kontribusi energi terbarukan sebesar 34% dalam pembangkitan listrik, dan mencapai emisi nol bersih di sektor ini pada tahun 2050 (UNDP, n.d.). Dalam rencana komprehensifnya, JETP (2023) menargetkan untuk menghentikan secara dini 1,7 GW pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2040, mencapai puncak emisi sektor listrik on-grid pada tahun 2030, tingkat emisi tidak lebih dari 250 MTonCO2-eq pada tahun 2030, pangsa energi terbarukan pada pembangkit listrik sebesar 44% pada tahun 2030, dan mencapai emisi nol bersih di sektor listrik pada tahun 2050.
Selain dari sektor kelistrikan, upaya mitigasi di bawah ENDC juga mencakup bisnis ekstraksi hulu. ENDC melihat reklamasi pasca-tambang seluas 81.069 hektare di bawah skenario tanpa syarat untuk pengurangan emisi dari sektor energi dan lebih banyak target yang tidak ditentukan dalam skenario bersyarat. Sementara itu, di sektor IPPU, upaya mitigasi yang direncanakan antara lain implementasi landfill gas (LFG) recovery, pengolahan limbah industri, serta pemanfaatan sampah sebagai sumber energi melalui Refuse Derived Fuel (RDF) dan pembangkit listrik tenaga biomassa.
Selama penelitian lapangan yang dilakukan sepanjang tahun 2020-2023, tim kami berusaha memahami bagaimana dinamika pasokan dan rantai nilai di pertambangan timah dan perkebunan kelapa sawit juga mempengaruhi perubahan iklim. Dari hasil wawancara dan diskusi dengan para pemangku kepentingan utama di kedua sektor tersebut, kami menyimpulkan bahwa terdapat banyak praktik yang menimbulkan kekhawatiran terkait target pengurangan emisi.
Di sektor timah, kami memahami bahwa peleburan dan pemurnian akan terus menerus membutuhkan batu bara untuk bahan bakar tungku selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Penggunaan panel surya telah berkembang di Bangka. Namun, sepengetahuan kami, hal ini masih terbatas pada penggunaan di dalam kantor dan kendaraan listrik. Di satu sisi, penggunaan batu bara oleh industri untuk menyalakan tungku mencerminkan target pengurangan emisi dari sektor energi, yang tidak mungkin mereda hingga nol bahkan setelah negara mencapai periode nol emisi bersih. Di sisi lain, hal ini juga berarti bahwa sumber-sumber berbasis fosil akan menjadi bahan “strategis” yang mendukung kebijakan hilirisasi atau hilirisasi di sektor pertambangan. Pada tahun 2009, Indonesia memperkenalkan Undang-Undang Pertambangan, yang mewajibkan semua produk mineral untuk diproses sebelum diekspor. Dalam implementasinya, kebijakan ini diterjemahkan ke dalam larangan ekspor bahan mentah dan tingkat kemurnian atau pemurnian minimum. Tujuan dari kebijakan ini termasuk mendorong kebijakan hilirisasi dalam negeri, industrialisasi, dan pelestarian komoditas tertentu untuk pemanfaatan nasional.
Selain masalah listrik, kami juga memahami bahwa peleburan dan pemurnian timah membutuhkan elemen tambahan, seperti aluminium dan seng, untuk mencapai tingkat kemurnian tertentu. Dari kunjungan kami ke fasilitas peleburan di Bangka, perusahaan mendaur ulang kaleng minuman ringan untuk mendapatkan unsur-unsur yang diperlukan yang kemudian dicampur untuk mendapatkan timah dengan tingkat kemurnian di atas 90%. Meskipun daur ulang menunjukkan pergerakan penggunaan material secara sirkuler, peraturan mengenai pengelolaan limbah masih perlu ditingkatkan sebagai bagian dari agenda dekarbonisasi nasional di sektor pertambangan. Salah satu isu yang perlu diperhatikan adalah limbah yang mengandung radioaktif yang tidak terkendali dari kegiatan peleburan dan pemurnian.
Penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung kini telah meluas secara masif ke wilayah daratan, yang diyakini memiliki cadangan yang lebih besar. Dengan adanya perluasan tersebut, ekosistem laut dan perikanan terancam. Di bawah ENDC saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan strategi untuk perlindungan wilayah pesisir sebagai bagian dari upaya untuk membangun dan mempertahankan ketahanan ekosistem dan bentang alam. Namun demikian, strategi dan aksi tersebut masih berfokus pada pengendalian polusi (terutama plastik) dan ekosistem bakau. Masih kurangnya perhatian terhadap pengembangan karbon biru untuk mengantisipasi ekspansi pertambangan darat seperti timah.
Konservasi Keanekaragaman Hayati
Kesepakatan internasional utama mengenai perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem alami adalah tujuan Aichi, yang diusulkan dalam lingkup Konferensi Para Pihak ke-10 Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Negara-negara penandatangan Konvensi menyesuaikan tujuan nasional mereka dengan tujuan CBD dan menetapkan Strategi dan Rencana Keanekaragaman Hayati Nasional untuk periode 2011-2022. Tujuan Aichi mengikuti Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan pada periode 2002-2010, yang hampir tidak mengalami kemajuan dalam hal tujuan yang diusulkan.
Dalam artikel ini kami membahas kemajuan tujuan Aichi di tiga negara yang merupakan bagian dari sabuk tropis global, dengan mencoba memperdebatkan bagaimana tujuan Aichi dipengaruhi oleh model agrikultur global yang didasarkan pada produksi dan ekspor komoditas dari sabuk tropis ke wilayah utara dunia.
Wilayah Tapajós, Brazil
Brazil meratifikasi CBD pada 1994 dan memberlakukan Kebijakan Keanekaragaman Hayati Nasional pada 2002. Pada 2011, pemerintah federal, bekerja sama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat, peneliti, perwakilan masyarakat adat dan masyarakat tradisional, serta sektor swasta, melaksanakan sebuah inisiatif yang dikenal dengan Dialog Keanekaragaman Hayati: membangun tujuan Brazil untuk tahun 2020. Inisiatif ini, yang mencakup serangkaian lokakarya, berpuncak pada penyusunan target keanekaragaman hayati nasional untuk tahun 2020 dalam lingkup Rencana Keanekaragaman Hayati Strategis 2011-2020. Tujuan dan subtujuan yang diusulkan dalam lingkup lokakarya ini dibuka untuk konsultasi publik secara online untuk mengkonsolidasikan tujuan akhir dengan mempertimbangkan saran dan kritik dari konsultasi tersebut.
Pada 2013, Resolusi CONABIO no. 06 mengatur tujuan nasional untuk konservasi keanekaragaman hayati terkait dengan Tujuan Aichi. Pada tahun yang sama, sebuah jaringan organisasi sukarela dari berbagai sektor masyarakat, PanelBio, dibentuk, yang misinya adalah mempromosikan pencapaian tujuan nasional. Pada 2017, revisi Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional (NBSAP) telah selesai dan diterbitkan. Tujuan keanekaragaman hayati nasional untuk periode 2011-2020 dibagi menjadi 5 tujuan utama, yaitu:
- Mengatasi akar penyebab hilangnya keanekaragaman hayati
- Mengurangi tekanan langsung terhadap keanekaragaman hayati dan mengganggu pemanfaatan berkelanjutan
- Memperbaiki situasi keanekaragaman hayati dengan melindungi ekosistem, spesies, dan keanekaragaman genetik
- Meningkatkan manfaat keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem untuk semua
- Meningkatkan implementasi melalui perencanaan partisipatif, manajemen pengetahuan, dan pengembangan kapasitas
Penyusunan tujuan keanekaragaman hayati nasional dan NBSAP dilakukan dengan berbagai metode partisipatif untuk mewakili berbagai kepentingan masyarakat Brazil. Meskipun metodologinya dianggap sebagai acuan bagi negara lain, beberapa tujuan berbenturan langsung dengan proyek-proyek pembangunan nasional dan investasi.
Dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian dan produksi serta ekspor komoditas, target nasional keanekaragaman hayati no. 3 dan no. 5 bertentangan dengan apa yang terjadi dalam praktiknya pada periode 2011 hingga 2020.
Tujuan nasional no. 3 bertujuan untuk mengurangi subsidi yang tidak tepat yang dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati, untuk meminimalisir dampak negatif. Di sisi lain, tujuan ini mengusulkan (bukan secara kuantitatif) desain dan penerapan insentif positif untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan sesuai dengan CBD. Secara global, menurut laporan Global Biodiversity Outlook, subsidi sekitar US$500 miliar telah mendorong kegiatan yang mengancam ekosistem dan keanekaragaman hayati. Menurut jaringan Climate Land Ambitions and Rights Alliance, insentif dan subsidi langsung dan tidak langsung untuk pertanian di wilayah dengan tingkat deforestasi tinggi seperti Chaco di Paraguay, Cerrado di Brazil dan Argentina Utara merugikan keanekaragaman hayati, hutan, dan hak-hak masyarakat tradisional serta masyarakat adat, dengan cara merampas tanah dan hutan mereka. Di sisi lain, perusahaan agribisnis besar menerima semua manfaat ekonomi. Di Brazil, kredit pedesaan untuk petani kecil & masyarakat tradisional dibandingkan dengan bisnis pertanian secara historis memiliki perbedaan yang sangat besar. Peningkatan ketersediaan kredit untuk agribisnis meningkat 140% dalam satu dekade, melonjak dari R$ 100 miliar (US$ 20,2 miliar) menjadi R$ 239 miliar (US$ 48,1 miliar).
Selain ketersediaan kredit pedesaan yang tinggi dengan suku bunga rendah dan persyaratan pembayaran utang yang istimewa, pembebasan dan pengurangan pajak dalam penjualan, industrialisasi, impor, dan penggunaan pestisida di Brazil sangat besar. Sebuah studi yang dikembangkan oleh Fio Cruz Foundation memperkirakan, pada tahun 2017, bahwa insentif positif untuk pupuk dan pestisida di Brazil pada saat itu mewakili total R$8,16 miliar lebih sedikit di kas pemerintah. Saat ini, pemberian pembebasan pajak untuk pestisida sedang dipertanyakan di Mahkamah Agung Federal (STF). Pengurangan 60% dalam pajak ICMS (Pajak Peredaran Barang dan Jasa Antarnegara Bagian dan Transportasi Antarkota dan Layanan Komunikasi) untuk pestisida di antarnegara bagian dan dalam operasi internal sedang dipertanyakan, serta pemberian pembebasan total pajak atas produk industri (IPI) untuk pestisida.
Tujuan keanekaragaman hayati nasional yang penting lainnya adalah tujuan keanekaragaman hayati nomor 5 yang sangat bertentangan dengan ekspansi bisnis pertanian untuk ekspor komoditas. Tujuan nomor 5 mengusulkan pengurangan 50% hilangnya ekosistem alami dan pengurangan degradasi serta fragmentasi vegetasi di seluruh bioma terestrial Brazil antara tahun 2010 dan 2020. Meskipun secara umum hilangnya ekosistem alami di bioma Brazil menurun selama periode ini, di beberapa bioma, angka tersebut mulai meningkat lagi setelah tahun 2017 dengan adanya kebijakan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Jair Bolsonaro.
Di Amazon, laju deforestasi meningkat 114% dari tahun 2010 hingga 2022. Dalam kasus Pantanal, laju deforestasi meningkat 19% pada periode yang sama dan di Cerrado, pusat perkebunan kedelai di Brazil, laju deforestasi meningkat sekitar 10%. Di wilayah Tapajós, hanya di Dataran Tinggi Santareno, area perkebunan kedelai meningkat 247%, melonjak dari 28 ribu hektare di tahun 2010 menjadi 99 ribu hektare di tahun 2021. Perluasan perkebunan kedelai di Amazon sebagian besar dilakukan di atas area terdegradasi (lahan padang rumput), tetapi juga terjadi di area yang baru saja mengalami deforestasi seperti yang dilaporkan oleh Guardian (2022). Ketika kedelai menempati area padang rumput, deforestasi dan perampasan lahan meluas di bawah hutan publik dan hutan masyarakat adat serta masyarakat tradisional, sehingga menciptakan lingkaran kehancuran. Dalam lingkaran ini, kedelai masuk ke padang rumput dan padang rumput masuk ke hutan, setelah beberapa tahun penggembalaan dan pengaturan lahan, lahan milik pribadi yang telah diatur tersebut dibeli oleh produsen kedelai, sehingga menimbulkan tekanan untuk area penggembalaan baru (Amazonia Latitute, 2021). Dua pendorong utama deforestasi di Brazil sepenuhnya terkait dengan produksi komoditas untuk ekspor, yaitu daging sapi dan kedelai (TRASE, 2022).
Setelah COP 15 di Montreal, kemunduran dan kegagalan tujuan Aichi global dan nasional kembali dihadapi. Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Pasca 2020, misalnya, mengusulkan perlunya penghapusan atau pengalihan subsidi dan insentif terkait keanekaragaman hayati dan pihak-pihak yang menjaganya, seperti masyarakat adat dan masyarakat tradisional di Brazil. Selama masih ada negara dan sektor swasta yang membiayai dan menerima pembiayaan secara langsung dan tidak langsung untuk perluasan model pertanian industri di Brazil, target keanekaragaman hayati yang baru akan tetap tidak efektif.
Putumayo, Kolombia
Kolombia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Karena lokasi geografisnya dan keragaman bioma di sepanjang garis pantai Pasifik dan Karibia, Cordilleras dan lembah Andes, dataran timur sabana Orinoquia, dan hutan Amazon.
Kolombia adalah penandatangan Konvensi Keanekaragaman Hayati dan akan menjadi tuan rumah COP CBD berikutnya pada tahun 2024. Pada Juni 2021, Sistem Nasional Kawasan Lindung (SINAP) Kolombia telah memperluas cakupannya menjadi 16,61% dari wilayah daratan (16,61%) dan 13,40% dari wilayah lautnya, yang berarti telah melampaui target Aichi untuk melestarikan 10% wilayah laut dan pesisir dunia, tetapi masih jauh dari target untuk melindungi 17% wilayah daratannya (CBD, 2021).
Meskipun demikian, sebagian besar (hampir 50% di wilayah Amazon) dari wilayah daratan Kolombia secara hukum ditetapkan sebagai wilayah Pribumi dan Afro-Kolombia, yang merupakan hak kepemilikan tanah kolektif yang diatur dalam Konstitusi (Konstitusi Kolombia , 1991)[1]. Meskipun beberapa wilayah ini mungkin tumpang tindih dengan kawasan lindung, sebagian besar berada di luar kawasan lindung, tetapi memberikan tingkat perlindungan tertentu untuk ekosistem dan keanekaragaman hayati.
Namun, terlepas dari perluasan kawasan lindung dan sertifikat tanah legal yang dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat adat dan masyarakat afro-kolombia, perluasan perbatasan komoditas tidak menghormati batas-batas ini. Perampasan tanah secara ilegal telah dilaporkan terjadi di dalam taman nasional dan merambah ke wilayah adat, yang mengakibatkan pemindahan dengan kekerasan dan konflik. konflik. (Volckhausen, 2019)[2]. Terlepas dari konsekuensi sosial ini, perubahan penggunaan lahan dan deforestasi yang disebabkan oleh perluasan peternakan, pertambangan, dan perkebunan koka juga menyebabkan penurunan populasi spesies liar, fragmentasi ekosistem, dan hilangnya koridor ekologi biologis penting yang menghubungkan Andes Cordillera dengan dataran rendah Amazon. Ancaman terhadap konektivitas ekologis menjadi perhatian khusus di Putumayo dan memengaruhi konektivitas budaya dan spiritual yang tertanam dalam pandangan dunia banyak kelompok masyarakat adat yang tinggal di wilayah Andes-Amazon (Samper dan Krause, 2024)[3].
[1]
Volckhausen, T. (2019). Perampasan lahan dan peternakan merusak Amazon Kolombia setelah demobilisasi FARC. Mongabay. Diambil pada 20 Juli dari. Periksa di sini.
[2]
Samper, J. A., & Krause, T. (2024). “Kami berjuang sampai akhir”: Tentang kekerasan terhadap pemimpin sosial dan pembela teritorial selama periode pasca-perjanjian damai dan implikasi ekologi politiknya di Putumayo, Kolombia. Pembangunan Dunia, 177, 106559. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106559
Ruette-Orihuela, K., Gough, KV, Vélez-Torres, I., & Martínez Terreros, CP (2023). Nekropolitik, pembangunan perdamaian, dan kekerasan rasial: Penyingkiran para pemimpin adat di Kolombia. Political Geography, 105, 102934. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2023.102934
Murillo-Sandoval, P. J., Kilbride, J., Tellman, E., Wrathall, D., Van Den Hoek, J., & Kennedy, R. E. (2023). Ekspansi pasca-konflik pertanian koka dan peternakan ilegal di Kolombia. Laporan Ilmiah, 13(1), 1965. https://doi.org/10.1038/s41598-023-28918-0
Vanegas-Cubillos, M., Sylvester, J., Villarino, E., Pérez-Marulanda, L., Ganzenmüller, R., Löhr, K., Bonatti, M., & Castro-Nunez, A. (2022). Perubahan tutupan hutan dan kebijakan publik: Sebuah tinjauan literatur untuk Kolombia pasca-konflik. Land Use Policy, 114, 105981. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.105981
Salazar, A., Sanchez, A., Dukes, J. S., Salazar, J. F., Clerici, N., Lasso, E., Sánchez-Pacheco, S. J., Rendón,Á. M., Villegas, J. C., Sierra, C. A., Poveda, G., Quesada, B., Uribe, M. R., Rodríguez-Buriticá, S., Ungar, P., Pulido-Santacruz, P., Ruiz-Morato, N., & Arias, P. A. (2022). Perdamaian dan lingkungan di persimpangan jalan: Pemilu di titik rawan keanekaragaman hayati yang bermasalah dengan konflik. Environmental Science & Policy, 135, 77-85. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.04.013
[3]
Samper, J. A., & Krause, T. (2024). “Kami berjuang sampai akhir”: Tentang kekerasan terhadap pemimpin sosial dan pembela teritorial selama periode pasca-perjanjian damai dan implikasi ekologi politiknya di Putumayo, Kolombia. Pembangunan Dunia, 177, 106559. Periksa di sini.
Bangka Belitung dan Kalimantan Barat
a) Minyak Kelapa Sawit
Dalam rantai komoditas minyak kelapa sawit global, Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar. Menurut laporan resmi Pemerintah Indonesia, produksi minyak kelapa sawit mencapai 48,68 juta ton dan menyediakan sekitar 16 juta lapangan pekerjaan serta mendukung perekonomian nasional dengan menyumbang hingga USD 18 juta dari total ekspor pada tahun 2018. Laporan resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian Indonesia, menyatakan bahwa total luas areal kelapa sawit mencapai 16,38 juta hektare pada tahun 2019. Dalam laporan tersebut, Kalimantan Barat menjadi daerah ketiga terluas dengan tutupan kelapa sawit di Indonesia dengan luas 1,80 juta hektare, sementara luas tutupan kelapa sawit terbesar berada di Riau dengan 3,38 juta hektare dan disusul oleh Sumatera Utara dengan luas tutupan 2,08 juta hektare.
Namun, kerugian dari memproduksi komoditas kelapa sawit telah melebihi manfaatnya, tidak hanya bagi masyarakat di lapangan, tetapi juga bagi lingkungan. Kunjungan kami ke Pontianak, Kalimantan Barat, salah satu daerah di Indonesia yang memproduksi minyak kelapa sawit dan memiliki area perkebunan kelapa sawit yang sangat luas, menemukan bahwa meningkatnya jumlah perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan perubahan penggunaan lahan secara besar-besaran dan mengurangi luas hutan di wilayah tersebut. Menurut Mongabay, sebuah kantor berita lingkungan, jumlah kawasan hutan di Kalimantan Barat telah berkurang 1,25 juta hektare antara tahun 2002 dan 2020, mengutip laporan Global Forest Watch. Meskipun demikian, merujuk pada laporan Global Forest Watch dalam artikel berita yang sama, laporan tersebut menyatakan bahwa hilangnya tutupan pohon belum tentu merupakan deforestasi, atau semata-mata disebabkan oleh perluasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Sebagai contoh, hal ini dapat dikaitkan dengan kondisi alam seperti badai, epidemi, atau kebakaran hutan.
Selain itu, ekspansi kelapa sawit di Indonesia telah meningkatkan perdebatan publik mengenai isu ekologi sejak awal tahun 2000-an, terutama mengenai hilangnya keanekaragaman hayati. Sebuah studi melaporkan bahwa ekspansi kelapa sawit yang memungkinkan terjadinya deforestasi di awal tahun 2000 telah mengancam atau bahkan mengurangi kekayaan populasi flora dan fauna endemik di Kalimantan Barat. Salah satunya yang menarik perhatian banyak ilmuwan adalah kasus kematian lebih dari ratusan ribu orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus), salah satu satwa endemik Pulau Kalimantan. Sebuah penelitian menyebutkan dengan jelas bahwa kepunahan banyak orangutan tersebut disebabkan oleh alih fungsi lahan (deforestasi) untuk perkebunan kelapa sawit skala industri dan aktivitas penebangan hutan untuk memenuhi kebutuhan industri pulp dan kertas.
Ekspansi perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan isu tentang perubahan agraria menjadi monokultur. Pola monokultur yang didorong oleh perkebunan kelapa sawit skala industri telah mengancam kekayaan spesies burung di Kalimantan Barat. Sebuah penelitian mencatat bahwa perkebunan kelapa sawit menjadi area vegetasi yang paling dihindari oleh kawanan burung, yang dapat membuat banyak spesies terancam punah. Hal ini tentu saja berkontribusi pada hilangnya kekayaan spesies burung di wilayah ini. Selain itu, banyak dari perkebunan industri yang diklaim berkelanjutan melalui skema standarisasi (misalnya, RSPO), pada kenyataannya tidak semuanya memiliki kriteria seperti yang diberikan label tersebut. Jika tidak, ekspansi kelapa sawit dalam skala industri justru mengancam kekayaan spesies endemik di wilayah Kalimantan Barat.
b) Timah
Indonesia adalah salah satu produsen timah terbesar di dunia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki cadangan terbesar kedua yang diperkirakan mencapai 800.000 ton dan produsen timah terbesar kedua di dunia. Timah yang terkandung di dalam batuan dan tanah diperkirakan jauh lebih tinggi, mencapai 0,693 pon per ton kubik dibandingkan dengan Malaysia, mengutip sebuah survei yang dilakukan oleh USGS pada tahun 1969. Hampir seluruh penambangan timah di Indonesia dihasilkan di Pulau Bangka dan Belitung yang telah menjadi lokasi penambangan timah sejak zaman penjajahan Belanda. Hal ini dapat dimaklumi karena Provinsi Bangka Belitung merupakan bagian dari kawasan sabuk timah di kawasan Asia Tenggara yang membentang dari Myanmar hingga Indonesia.
Produksi dan pengelolaan komoditas timah di Indonesia dapat dikatakan sangat tersentralisasi dengan PT Timah sebagai produsen terbesar. Perusahaan ini memiliki total 473.388 hektare area pertambangan dengan 127 izin usaha pertambangan (IUP) yang tersebar di 184.672 hektare lepas pantai dan 288.716 hektare di darat. Menurut International Tin Association, pada tahun 2022 PT Timah memproduksi 19.800 ton yang menurun 25,3% dari tahun 2021 yang memproduksi 26.000 ton, yang mungkin dipengaruhi oleh kebijakan pelarangan ekspor (hilirisasi). Namun, pihak swasta juga terlibat dalam ekstraksi dan pengolahan dengan mendirikan smelter dan memiliki area pertambangan.
Kunjungan tim EPICC Indonesia ke Pulau Bangka dan Belitung menemukan bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menggantungkan hidupnya pada timah. Selain karena harganya yang cukup menarik di pasaran, penambangan bijih timah juga dapat dilakukan dengan mudah oleh masyarakat setempat dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Sayangnya, praktik penambangan timah di Bangka Belitung banyak dikecam karena memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Misalnya, banyaknya lubang-lubang bekas tambang yang tidak terurus akibat tidak ditegakkannya kebijakan reklamasi pascatambang. Kerusakan lingkungan juga meluas tidak hanya di daratan tetapi juga di lautan, karena pergeseran area penambangan akibat penipisan timah di daratan. Selain itu, perluasan penambangan ke lepas pantai juga meningkatkan tensi konflik antar masyarakat.
Selama kunjungan tim EPICC Indonesia ke Bangka dan berinteraksi dengan nelayan setempat, penambangan lepas pantai menjadi ancaman bagi kehidupan laut dan terumbu karang, terutama karena kegiatan penambangan lepas pantai. Penambangan timah lepas pantai ini merusak karena umumnya menggunakan kapal-kapal besar dan kapal keruk untuk penambangan industri, dan ratusan ponton yang dibangun oleh para penambang tradisional. Seorang nelayan yang kami wawancarai menginformasikan bahwa telah terjadi penurunan jumlah ikan yang ditangkap, baik dari segi jumlah maupun jenisnya, dan banyak nelayan yang harus melaut lebih jauh untuk menangkap ikan. Pengamatan EPICC Indonesia juga menemukan bahwa laut dan daerah tangkapan ikan telah berubah menjadi keruh karena proses penyedotan dalam penambangan timah.
Selain itu, ada banyak penelitian dan literatur abu-abu yang melaporkan dampak penambangan timah terhadap keanekaragaman hayati. Sebagai contoh, sebuah penelitian menemukan bahwa ekstraksi tambang timah di Bangka dan Belitung telah mengancam kerapatan hutan bakau yang sangat penting bagi daerah pesisir sebagai sebuah pulau. Penambangan timah juga dilaporkan telah mengancam keberadaan Arwana Kelesak, spesies air tawar endemik. Selain itu, penambangan tersebut telah merusak tanah di Bangka Belitung mulai dari kerusakan struktur tanah hingga hilangnya bahan organik tanah dan kesuburannya. Penambangan lepas pantai juga menyebabkan sedimentasi di hilir sungai dan hilangnya vegetasi sehingga membahayakan terumbu karang di Tanjung Pandan.
Peraturan bebas deforestasi Uni Eropa (EUDR)
EUDR sebagai koneksi yang menyimpang?
Dalam upaya untuk memahami secara lebih baik dan kritis hubungan antara Uni Eropa sebagai wilayah konsumsi dan wilayah ekstraksi, kelompok EPICC memutuskan untuk fokus pada Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR) sebagai contoh terbaru dari intervensi tata kelola publik-swasta di mana kekuasaan dan keterkaitan ditelusuri dan dinamika teritorial diubah oleh keputusan-keputusan yang diambil jauh di dalam rantai tersebut, yaitu di dalam ruang regulasi, politik dan sosial-ekonomi Eropa. Pilihan ini sesuai dengan tujuan EPICC untuk mengidentifikasi dan menganalisis titik-titik pengungkit (chokepoints) dan titik-titik buta (blind spots), serta menjelaskan kondisi mikro dan makro yang dapat memfasilitasi mitigasi dampak lingkungan dan sosial yang terjadi di lokasi ekstraksi dan produksi yang dipilih (di Brazil, Kolombia, dan Indonesia).
Seri blog yang tersedia di situs web kami merupakan hasil penelitian selama lebih dari satu tahun yang dilakukan oleh para peneliti EPICC, dan khususnya dari enam belas wawancara semi-terstruktur dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam EUDR, konseptualisasinya, dan proses politik yang melingkupinya. Wawancara ini dilakukan selama empat bulan, bertepatan dengan negosiasi trilog tingkat Uni Eropa (UE) dan pengadopsian EUDR yang baru. Setiap wawancara berlangsung selama kurang lebih satu jam dan dilakukan melalui platform virtual. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan menginvestigasi perubahan kebijakan dan narasi yang sedang berlangsung melalui suara dan pengalaman para aktor yang terlibat langsung dalam promosi, diskusi, dan pendefinisian peraturan tersebut.
Para peneliti bertujuan untuk menggabungkan berbagai perspektif dan suara. Meskipun ada beberapa kesulitan yang dihadapi dalam proses penelitian, seperti penolakan wawancara oleh beberapa aktor terkemuka di Uni Eropa, proses ini masih memberikan wawasan berharga tentang tingkat keterlibatan dan kesediaan para aktor tersebut untuk berpartisipasi dalam diskusi yang berkaitan dengan EUDR. Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan lima wawancara dengan individu dari organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil, lima wawancara dengan aktor publik Uni Eropa, tiga wawancara dengan perwakilan negara di Uni Eropa, dan tiga wawancara dengan aktor sektor swasta (yang terdiri dari dua dari skema sertifikasi yang terkemuka dan satu dari asosiasi sektor ritel). Berbagai sudut pandang ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses implementasi dan membantu mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam proses yang sedang berlangsung ini.
Melalui serangkaian publikasi singkat ini, kami ingin berkontribusi terhadap berbagai diskusi yang sedang berlangsung sehubungan dengan pembongkaran peraturan dan implementasinya. Berbeda dengan perdebatan lainnya, fokus kami lebih dari sekadar kepraktisan dan detail teknis: kami menempatkan EUDR dalam kompleksitas proses historis dan politis-ekologis yang terjadi di wilayah produksi, serta menanyakan potensi dan keterbatasan yang muncul dari intervensi Eropa.
Blog pertama memberikan tinjauan umum dan kritis terhadap EUDR sebagai intervensi terbaru dan inovatif secara hukum dalam tata kelola rantai pertanian-pangan global. Dalam tulisan ini, kami menyoroti elemen-elemen prosedural dan substantif utama dari Peraturan tersebut, untuk memfasilitasi pemahaman tentang diskusi yang sedang berlangsung di dalam dan di luar dunia akademis. Pada saat yang sama, kami membuat sketsa ruang lingkup intervensi kritis yang terkandung dalam blog berikut ini dan yang menyangkut latar belakang peraturan, persyaratan prosedural, gagasan substantif yang diadopsi, dan implementasinya.
Blog kedua membahas rincian EUDR sebagai ‘peraturan ekologi’, yaitu sebuah peraturan yang akan memiliki implikasi dan konsekuensi terhadap proses dan praktik sosial dan lingkungan di negara asal tujuh komoditas yang tercakup di dalamnya. Melalui gagasan ‘shift‘, kami menyarankan bahwa peraturan tersebut, meskipun tidak mengatur perilaku apa pun di luar perbatasan Uni Eropa, akan menciptakan insentif positif dan negatif untuk lima pergeseran yang mungkin terjadi: pergeseran dari ekspor/produksi ke pasar Uni Eropa ke pasar lain yang tidak mengatur deforestasi dengan cara yang sama; pergeseran deforestasi ke ekosistem lain yang saat ini tidak tercakup dalam definisi bebas deforestasi, namun mungkin akan tercakup di masa depan; pergeseran ke komoditas lain yang tidak tercakup dalam cakupan peraturan tersebut, namun mungkin akan tercakup di masa depan; pergeseran kepemilikan lahan dan intensifikasi konsentrasi; dan pergeseran dari produksi untuk ketahanan pangan/ kemandirian pangan lokal ke arah produksi tanaman pangan untuk pasar Eropa.